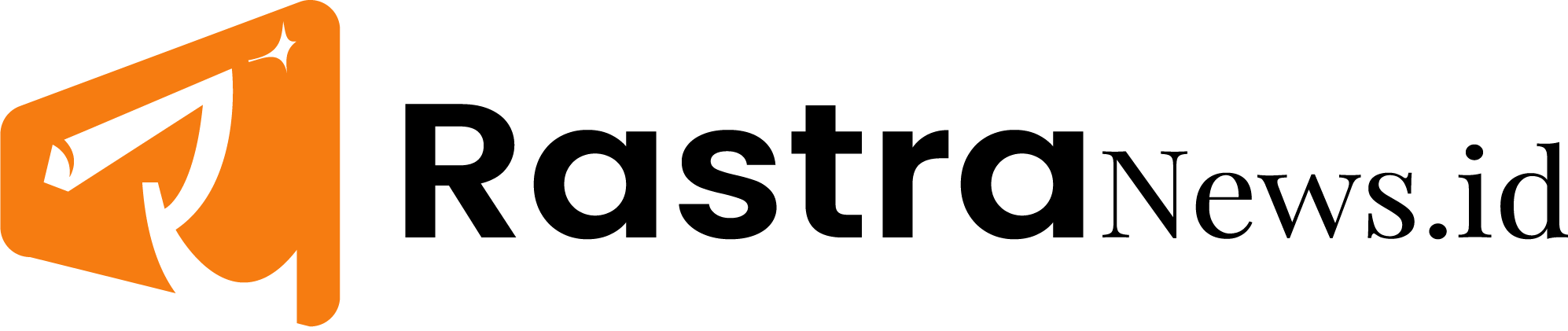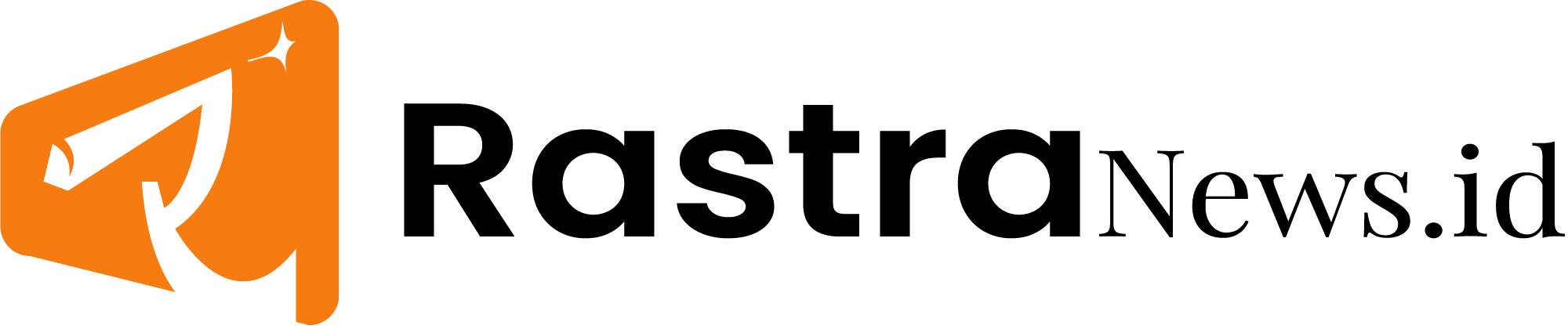ᨑᨗᨈᨘᨕ ᨆᨅᨙᨉ ᨅᨚᨒ ᨉᨗ ᨔᨘᨒᨓᨙᨔᨗ ᨔᨙᨒᨈ ᨖᨅᨘᨂ ᨕᨈᨑ ᨍᨙᨍ ᨈᨂ ᨉᨗ ᨑᨘᨆ ᨈᨙᨑᨉᨗᨔᨗᨕᨚᨊ ᨉ ᨌ ᨈᨂ ᨉᨗ ᨁᨚᨕ ᨄᨙᨑᨔᨙᨍᨑ
SULSEL – Di tengah derap pembangunan dan gaya hidup serba modern, masih ada tradisi yang bertahan dalam senyap. Di berbagai pelosok Sulawesi Selatan, ketika sebuah rumah baru selesai dibangun, pemiliknya tidak serta-merta memindahkan perabot atau menempatinya.
Mereka justru memanggil seorang sanro bola (dukun rumah) untuk memulai satu prosesi sakral yang disebut Mabedda Bola.
Secara harfiah, Mabedda Bola berarti “memberi bedak pada rumah”. Tapi maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar kosmetik arsitektur. Ini adalah ritual penyucian, perlindungan spiritual, sekaligus penanda bahwa rumah tersebut telah “diisi” dengan doa dan harapan.
Salah satu simbol paling khas dalam ritual ini adalah cap telapak tangan—yang ditempelkan di tiang utama rumah atau pada bagian strategis lainnya. Telapak tangan yang dicelupkan dalam ramuan alami ini seolah menjadi tanda tangan spiritual sang penghuni kepada semesta.
Ramuan untuk mencetak tangan ini bukan sembarang bahan. Biasanya terdiri dari tepung beras, kunyit, air, dan sesekali ditambah parutan lengkuas. Semuanya diolah secara khusus oleh sanro, lalu dilumurkan ke tangan yang akan dicapkan.
Menariknya, tidak semua orang boleh mencetak tangan mereka. Dalam banyak kasus, hanya perempuan muda yang belum menstruasi atau anggota keluarga yang dianggap suci yang dipercaya melakukan cap tangan tersebut. Ini menandakan kesucian dan harapan baik.
Cap tangan ini kemudian ditempelkan di possi bola—tiang utama rumah yang dianggap sebagai pusat kekuatan dan perlindungan. Setelah itu, proses bisa dilanjutkan di tempat-tempat lain seperti tangga, ruang keluarga, bahkan dapur.
Bagi masyarakat Bugis-Makassar, tangan bukan sekadar alat kerja. Tangan melambangkan doa, niat, dan kekuatan batin. Maka, menandai rumah dengan tangan adalah cara meletakkan doa dan harapan secara harfiah ke dalam bangunan.
Menariknya lagi, rumah dalam kosmologi Bugis-Makassar tidak dianggap sekadar tempat tinggal. Rumah adalah miniatur semesta. Atap mewakili langit (Boting Langi’), lantai mewakili dunia tengah (Ale Kawa), dan kolong rumah mewakili dunia bawah (Buri Liu’).
Dengan demikian, cap tangan pada tiang rumah sejatinya adalah cap tangan pada alam semesta kecil yang akan menjadi tempat tinggal baru sang pemilik. Sebuah simbol keterikatan antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa.
Uniknya, tradisi cap tangan ini tidak hanya hadir dalam budaya rumah adat. Arkeolog menemukan bahwa lukisan tangan serupa juga ditemukan di gua-gua prasejarah di Sulawesi Selatan—khususnya di Maros, Pangkep, dan Bone.
Di gua-gua seperti Leang Timpuseng, ada stensil tangan berwarna merah yang berusia hingga 39.000 tahun. Cara pembuatannya serupa: tangan diletakkan di dinding lalu disemprot dengan pewarna alami. Fungsinya pun mirip—menandai ruang dan menunjukkan eksistensi.

Kemiripan antara ritual Mabedda Bola dan lukisan tangan prasejarah ini menunjukkan kesinambungan budaya yang luar biasa panjang. Dari dinding gua ke tiang rumah, dari pewarna tanah ke bedak alami, maknanya tetap sama: “kami di sini, dan kami ingin selamat.”
Di beberapa daerah, praktik Mabedda Bola memiliki variasi lokal. Di Barru, misalnya, ritual dilakukan setelah Magrib dan hanya oleh perempuan muda. Di Bone, tangan digerakkan ke atas saat dicetak, memberi efek jari yang memanjang. Di Soppeng, hanya tiga jari yang dicetak sebagai lambang kerendahan hati.
Jumlah cap tangan pun bervariasi. Ada yang hanya satu di tiang utama, ada pula yang nyaris di setiap penjuru rumah. Semakin banyak cap, dipercaya semakin kuat perlindungan spiritualnya.
Proses ritual biasanya terdiri dari beberapa tahap. Dimulai dari mappassili atau penyucian rumah, lalu mappalleppe yaitu pemberian sesajen dan doa-doa, dan terakhir penempelan cap tangan. Semua tahapan ini dijalankan agar rumah bersih dari energi buruk dan siap ditinggali.
Namun, seiring waktu, beberapa hal berubah. Rumah kayu perlahan tergantikan rumah beton. Tiang-tiang kayu tempat mencetak tangan kini diganti dinding semen. Meski bentuknya berubah, makna dan semangatnya tetap dijaga.
Dulu, perempuan lebih sering mencetak tangan. Kini, kepala keluarga laki-laki pun mulai mengambil peran. Proses penyucian pun tidak selalu mengosongkan rumah sepenuhnya, sebagaimana dulu dilakukan.
Sayangnya, tidak semua generasi muda tahu atau peduli tentang tradisi ini. Sebagian menganggapnya kuno atau tidak relevan lagi. Padahal, Mabedda Bola bukan hanya tentang rumah, tapi juga tentang akar budaya dan spiritualitas leluhur.
Untungnya, beberapa komunitas budaya, akademisi, dan budayawan kini berusaha mendokumentasikan dan menghidupkan kembali tradisi ini. Mereka meyakini, bahwa selama masih ada tangan yang ingin mencetak harapan, Mabedda Bola akan terus hidup.
Jejak tangan itu, meski sederhana, sesungguhnya adalah simbol dari peradaban yang panjang. Tangan yang menandai rumah bukan hanya menandai kayu, tapi menandai sejarah, doa, dan keberadaan manusia dalam semesta.
Dan setiap kali kita melihat cap tangan itu di tiang rumah atau di dinding gua, kita diingatkan akan satu hal: bahwa manusia selalu ingin meninggalkan jejak, bukan untuk dikenang semata, tapi untuk merasa terhubung—dengan leluhur, dengan tanah, dan dengan yang ilahi.