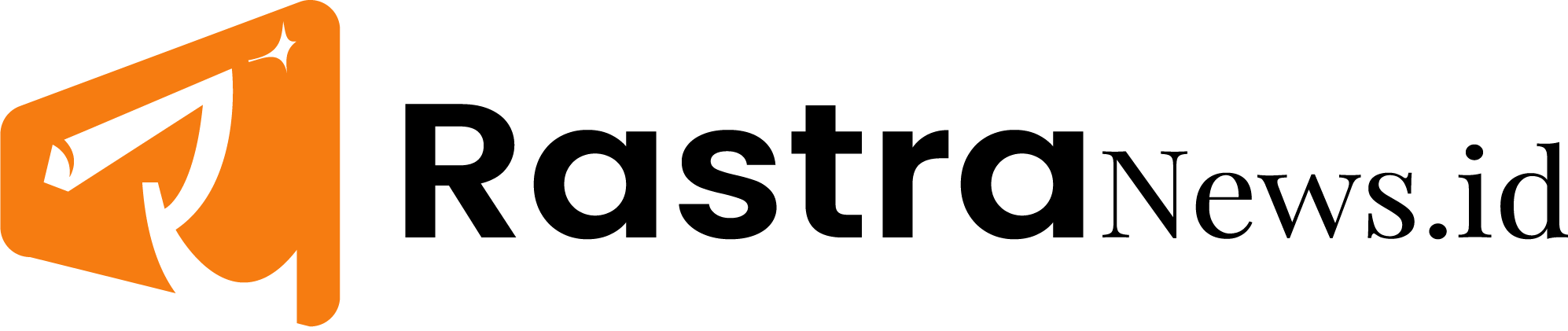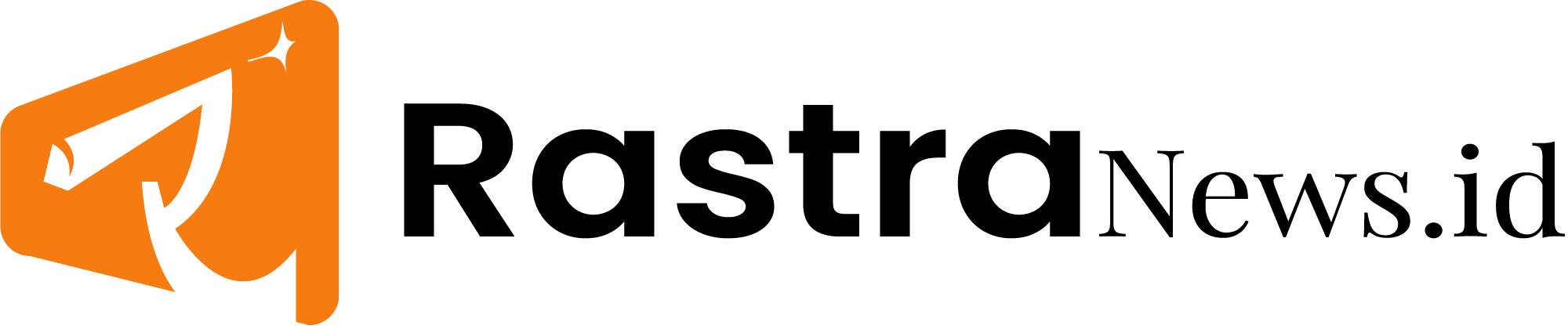Meski begitu, Asratillah mengingatkan potensi bias dalam penerapan sistem ini.
Ada kekhawatiran representasi perempuan dalam proses politik ini menjadi semakin melemah.
“Sistem ini juga berpotensi memperkuat bias patriarki dan eksklusivitas, sebab dalam praktik sosial, kepala keluarga sering kali dimaknai sebagai laki-laki, sehingga representasi perempuan dan kelompok marginal dalam proses politik lokal menjadi semakin lemah,” tambahnya.
Ia juga menyoroti ketentuan dalam Perwali yang menempatkan pemilihan Ketua RW melalui para Ketua RT terpilih.
Secara administratif hal ini memang lebih efisien, tapi menurut Asratillah, ini juga berpotensi menciptakan lingkungan oligarki. Konsekuensi dari mekanisme tersebut dapat membuat RW lebih loyal kepada birokrasi ketimbang kepada warga.
“Secara politik, hal ini bisa menciptakan sistem oligarkis mini, di mana pemilihan RW menjadi domain elit lokal (para ketua RT), bukan hasil aspirasi langsung masyarakat,” katanya.
Secara umum, Asratillah menilai Perwali Nomor 19 Tahun 2025 memperlihatkan tarik-menarik antara efisiensi administratif dan ideal demokrasi partisipatoris.
Namun di satu sisi, regulasi ini juga menertibkan proses pemilihan agar tidak terlalu rumit dan berpotensi konflik.
“Tetapi di sisi lain, ia juga mempersempit ruang partisipasi politik warga di tingkat mikro,” tuturnya.
Lebih lanjut, Asratillah pun menekankan pentingnya keseimbangan antara dua hal tersebut.
Caranya dengan memperkuat pendidikan politik masyarakat, memperjelas mekanisme akuntabilitas RT/RW, serta membuka kanal evaluasi publik pasca pemilihan.
“Demokrasi lokal tidak hanya diukur dari cara memilih, tetapi juga dari sejauh mana warga bisa mengontrol dan menilai kinerja pemimpin lingkungannya,” pungkasnya. (MA)