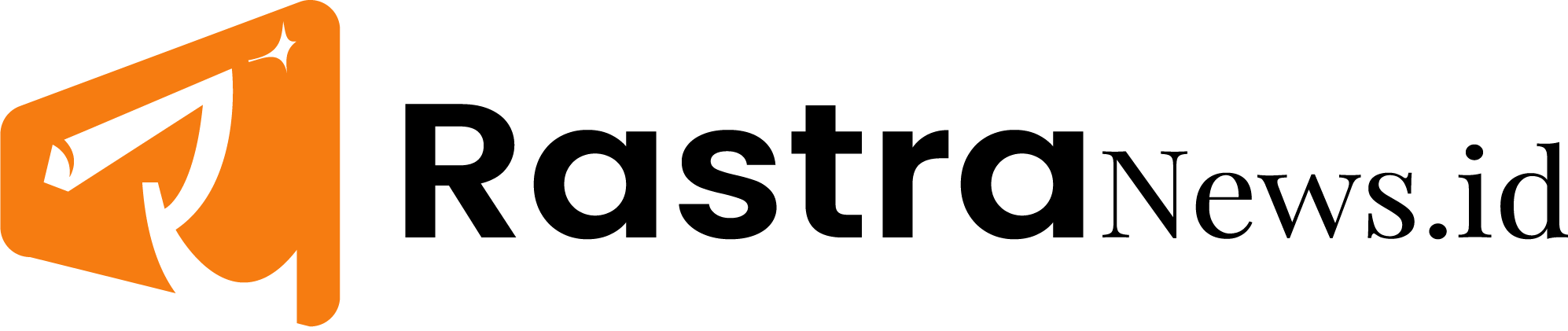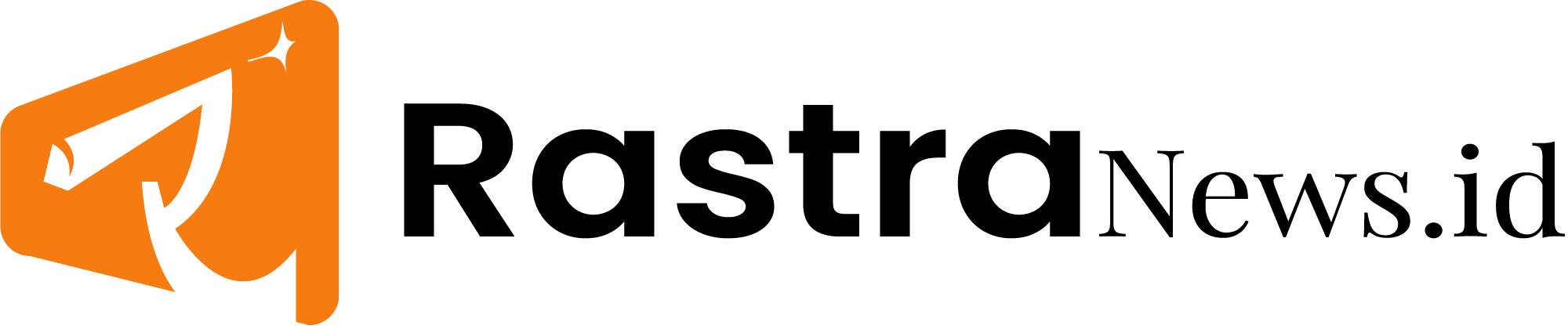Rastranews.id, Makassar – Pagi itu, Jalan Urip Sumoharjo, arteri utama Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sudah riuh oleh deru kendaraan.
Namun, di antara kemewahan mobil dan gedung-gedung pencakar langit, terpampang pemandangan lain yang tak kalah akrab: sosok-sosok yang bertarung dengan kerasnya kehidupan di trotoar.
Mereka adalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal dan gepeng) yang menjadi bagian dari wajah urban kota metropolitan.
Salah satunya adalah Daeng Ngai (60). Dengan tekun, perempuan sepuh itu mendorong gerobak kayunya yang sederhana.
Setiap hari, ia menempuh perjalanan panjang berjalan kaki dari rumahnya di Adyaksa Baru menuju kawasan Urip Sumoharjo. Jumat adalah hari istimewa; ia memulai aktivitas lebih pagi.
“Hari biasa jam 2 baru keluar, magrib pulang,” ujarnya, menceritakan jam kerjanya dengan polos, seolah menggambarkan sebuah profesi formal yang ia lakoni selama dua tahun terakhir.
Di balik kerutnya, tersimpan cerita. Daeng Ngai terpaksa turun ke jalan karena tidak ada lagi suami yang menafkahi. “Tidak ada suami cari uang,” katanya singkat.
Kini, ia hanya hidup berdua dengan anak bungsunya, berusaha mempertahankan napas kehidupan.
Sebagai upaya meringankan beban, pemerintah memberikannya Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras.
Namun, bantuan yang datang hanya setiap 2-3 bulan sekali itu bagai setetes air di padang pasir. “Tidak pernah cukup,” mungkin adalah ungkapan yang terpatri dalam benaknya, meski tak terucap.
Yang lebih menyentuh, Daeng Ngai mengaku tidak pernah sekalipun merasakan program pembinaan atau pemberdayaan dari pemerintah. Hanya dua kata pendek yang ia ucapkan ketika ditanya: “Tidak pernah.”
Keberadaan Daeng Ngai dan ratusan lainnya seperti dia adalah cermin dari persoalan sosial-ekonomi yang masih mengakar di tengah gemerlap Makassar.
Mereka bukan sekadar statistik atau gangguan estetika kota, melainkan manusia yang terjepit dalam lingkaran kemiskinan.
Merespons fenomena ini, Pengamat Pemerintahan Jalaludin B. menegaskan bahwa masalah ini adalah urusan konstitusional. Ia mengutip bunyi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 dengan tegas: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”
“Artinya, jika negara dalam arti pemerintah provinsi, meliputi Gubernur, Wali kota, dan Bupati, wajib memastikan bahwa kelompok rentan ini dapat memperoleh kebutuhan dasar mereka. Jika tidak, berarti pemerintah melakukan pelanggaran konstitusi,” jelas Jalaludin.
Ia menduga, desakan ekonomi adalah akar masalahnya. “Menjadi gelandangan, anak jalanan, dan seterusnya adalah cara termudah mendapatkan uang. Ada juga gap kelas sosial bahwa ukuran standar kehidupan yang baik itu adalah kepemilikan ekonomi yang cukup,” paparnya.
Jalaludin menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan bantuan langsung tunai (BLT). Ia merekomendasikan kebijakan yang mengakomodasi partisipasi sosial anak jalanan dengan upah yang memadai, tentu dengan memperhatikan usia dan kapasitas mereka.
“Misal, pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta keamanan dari orang dewasa yang tidak sedikit menggunakan anak-anak gelandangan ini untuk keperluan pribadi,” ujarnya.
Langkah seperti membuat jaminan sosial atau asuransi bagi kelompok rentan juga dinilai penting.
Ia juga menyoroti perbedaan paradigma, “Di Eropa ada kesan orang-orang rentan seperti gelandangan dianggap pemalas sehingga tidak ada kewajiban untuk memperhatikan mereka.”
Namun, sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, tanggung jawab sosial negara tidak bisa dielakkan.
Kisah Daeng Ngai adalah sebuah narasi yang berulang. Ia adalah pengingat bahwa di balik kemajuan sebuah kota, ada cerita-cerita yang tertinggal.
Maraknya anjal dan gepeng bukan hanya soal penertiban, tetapi lebih pada panggilan untuk penanganan yang manusiawi, berkelanjutan, dan konstitusional.
Sebuah tugas bersama untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga negara yang harus menjadikan trotoar sebagai tempat mencari harapan. (HL)